Oleh: Dian Istiqomah (Pemerhati Pangan, Anggota DPR RI 2019-2024)
Dominasi beras di Indonesia telah lama menjadi titik simpul masalah pangan nasional. Fenomena ini bukan sekadar preferensi budaya, melainkan warisan kebijakan terstruktur yang berakar dari program Revolusi Hijau Orde Baru—sebuah keberhasilan sekaligus kegagalan besar.
Keberhasilan diukur dari tercapainya swasembada beras pada era 1980-an; kegagalan terukur dari monokultur pangan, ketergantungan pada pupuk kimia, hingga terpinggirkannya komoditas lokal yang sejatinya lebih cocok untuk kondisi agroklimat beragam di Nusantara.
Masalah ketersediaan beras saat ini, yang ditandai dengan fluktuasi harga dan keterpaksaan impor, merupakan puncak gunung es dari kegagalan diversifikasi yang berlangsung selama puluhan tahun.
Di Nusa Tenggara Timur (NTT), ironi itu terlihat jelas: daerah kering dipaksa menanam padi, menciptakan defisit kronis, sementara sorgum, jagung, dan umbi-umbian diabaikan.
Upaya membangkitkan kembali pangan lokal, seperti yang giat dilakukan warga dan pemerintah daerah, adalah strategi yang cerdas untuk ketahanan regional. Namun, lantas apakah gerakan ini akan menjadi solusi mujarab untuk menstabilkan krisis beras di panggung nasional?
Sebuah analisis struktural-teknokratik menemukan jawabannya adalah tidak secara langsung. Optimisme terhadap pangan lokal sebagai penawar bagi masalah beras nasional terlalu disederhanakan.
Diversifikasi pangan tanpa intervensi sistematis hanya akan menciptakan “tambal sulam” regional tanpa menyelesaikan akar masalah struktural beras. Masalah utama bukan lagi soal apa yang ditanam, melainkan bagaimana sistem ekonomi dan logistik kita memproses, menyimpan, dan mendistribusikannya.
Ekonomi Pangan Lokal
Ketergantungan Indonesia pada beras adalah fenomena struktural yang didukung oleh keunggulan efisiensi ekonomi skala yang sulit ditandingi oleh pangan lokal. Beras mendominasi karena didukung sistem industri yang terintegrasi, mulai dari penggilingan modern, gudang berkapasitas besar milik Bulog, hingga jaringan distribusi yang terstandardisasi.
Pangan lokal, sebaliknya, berjuang dalam fragmentasi dan hambatan teknologi pascapanen. Ambil contoh sorgum. Meskipun sangat tahan kekeringan dan ideal di lahan marginal, pengolahan sorgum menjadi produk yang kompetitif memerlukan teknologi de-hull (pengupasan kulit) dan penggilingan yang mahal. Ini membuat cost of goods sold sorgum seringkali tidak kompetitif dibandingkan beras.
Sementara itu, umbi-umbian seperti singkong memiliki kelemahan logistik yang parah: daya simpannya yang sangat pendek (perishable) membuatnya tidak ideal untuk stok cadangan atau distribusi jarak jauh. Singkong membutuhkan volume dan berat yang lebih besar untuk mengirimkan jumlah kalori yang sama dengan beras, yang meningkatkan biaya logistik per energi.
Untuk mengatasi ini, diversifikasi harus didampingi intervensi negara yang terencana. Pertama, harus ada subsidi dan insentif untuk modernisasi teknologi pascapanen pangan lokal. Petani tidak akan beralih jika margin keuntungan dari komoditas lokal lebih rendah dan risikonya lebih tinggi.
Kedua, Bulog harus berfungsi sebagai offtaker dan penstabil harga untuk komoditas pangan lokal strategis selain beras, sehingga tercipta jaminan pasar bagi petani.
Ketiga, perlu ada standardisasi produk yang seragam, terutama untuk tepung komposit, agar pangan lokal dapat diserap oleh industri makanan olahan skala besar (misalnya, untuk mi atau roti) sebagai substitusi parsial yang kredibel.
Mengelola Risiko Beras
Selain memperkuat sisi suplai pangan lokal, negara juga harus mengelola sisi permintaan beras melalui kebijakan harga yang tepat. Salah satu akar masalah krisis pangan saat ini adalah beras tetap menjadi komoditas politikal yang harganya selalu dijaga agar terjangkau, terutama menjelang tahun politik.
Kebijakan ini, dikutip dari laporan lembaga riset INDEF, telah menciptakan distorsi pasar dan menekan insentif petani padi untuk berinvestasi dalam peningkatan produktivitas yang berkelanjutan. Petani memilih metode tanam cepat (dan seringkali merusak kualitas tanah) karena keuntungan mereka ditentukan oleh kuantitas, bukan kualitas.
Diversifikasi pangan akan efektif jika didukung oleh harga beras yang merefleksikan biaya produksi riil dan berkelanjutan. Selama beras dipatok murah melalui skema subsidi yang masif, masyarakat akan selalu memilih beras karena dianggap ekonomis dan praktis. Upaya revitalisasi pangan lokal justru bisa berisiko memperkuat stigma sosial—bahwa pangan lokal adalah makanan kelas bawah atau pilihan saat paceklik—jika harga beras terus-menerus dipertahankan di bawah nilai ekonomisnya.
Pemerintah perlu secara bertahap menyesuaikan harga acuan pembelian (HAP) gabah/beras untuk mendorong efisiensi dan investasi pada lahan-lahan sawah yang paling produktif. Pada saat yang sama, subsidi harus dialihkan dari komoditas (beras) ke konsumen, melalui program jaminan pendapatan atau bantuan sosial yang lebih terarah, yang memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah memilih sendiri sumber karbohidrat terbaik, termasuk pangan lokal yang mulai kompetitif.
Strategi ini akan menyeimbangkan pasar dan memastikan pangan lokal dapat bersaing secara sehat tanpa perlu melawan dominasi harga beras yang terdistorsi.
Pangan lokal bukan sekadar warisan budaya yang harus dibangkitkan, melainkan aset ekonomi strategis yang harus diintegrasikan ke dalam sistem pangan modern. Solusi konstruktifnya adalah menciptakan sistem yang adil dan efisien.
Keberhasilan NTT dalam mengurangi ketergantungan pada beras adalah model yang harus diduplikasi, tetapi harus disempurnakan dengan intervensi hulu-hilir di tingkat nasional. Tanpa reformasi struktural pada infrastruktur pascapanen dan tata kelola harga beras, revitalisasi pangan non-beras hanya akan meredakan defisit di beberapa kantong daerah, tetapi tidak akan secara fundamental menyelesaikan tantangan pangan pokok di panggung nasional. 23/10/2025
Red/amr

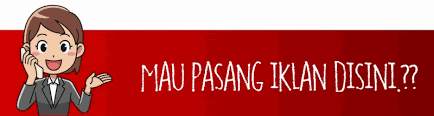


Discussion about this post