Oleh: Dian Istiqomah, Anggota DPR RI 2019-2024
Stok beras Indonesia yang mencapai rekor tertinggi 3,7 juta ton—bahkan diprediksi menembus 4 juta ton—adalah capaian produksi yang patut diapresiasi.
Namun, di tengah kelimpahan ini, harga eceran justru mengalami kenaikan 3,6% pada semester I-2024, dengan disparitas ekstrem terutama di Papua, di mana harga mencapai Rp16.904/kg jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp13.500.
Paradoks ini secara gamblang mengungkap tiga kegagalan sistemik yang mendasari masalah pangan nasional: distribusi yang timpang, kebijakan yang cenderung reaktif, serta ketergantungan akut pada beras sebagai komoditas pangan utama. (Sumber: Data Bapanas dan Kementerian Pertanian)
Distribusi Tersandera oleh Inefisiensi dan Kartel
Melimpahnya stok beras seharusnya menjamin stabilitas harga, namun praktik mafia rantai pasok justru menggerogoti ketersediaan ini di tingkat konsumen.
Investigasi gabungan Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, dan Satgas Pangan menemukan fakta mengejutkan: 95% beras medium dijual di atas HET, sementara 88% beras cacat mutu beredar bebas di pasar. Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), yang seharusnya menjadi barometer stabilitas pasokan, justru disinyalir menjadi episentrum distorsi.
Pasokan sebesar 11.410 ton per hari diduga raib akibat penimbunan spekulan, mengindikasikan adanya praktik kartel yang mengendalikan harga. Kebocoran ini diperparah oleh inefisiensi logistik yang kronis; di Nusa Tenggara Timur, misalnya, hanya satu transporter melayani seluruh kabupaten, memicu keterlambatan distribusi bantuan yang vital bagi masyarakat. (Sumber: Investigasi Kementan, Bapanas, Satgas Pangan; Data PIBC; Laporan Bantuan Pangan NTT)
Kebijakan Kontraproduktif dan Urgensi Reorientasi
Kebijakan relaksasi HET yang diperpanjang hingga Mei 2024 terbukti kontraproduktif. Alih-alih menstabilkan harga, kebijakan ini justru meninggikan HET beras premium menjadi Rp14.900/kg di Jawa dan Rp15.800/kg di Papua.
Pendekatan ini abai terhadap akar masalah yang sesungguhnya: tingginya biaya logistik dan margin tengkulak yang bisa mencapai 40%.
Kondisi ini semakin miris jika melihat alokasi anggaran; sebesar Rp16,6 triliun dialokasikan untuk serapan gabah petani, namun bantuan beras bagi masyarakat hanya mendapat Rp5 triliun, memperlebar ketimpangan akses pangan bagi 18,3 juta keluarga penerima manfaat.
Reorientasi kebijakan sangat diperlukan untuk memastikan subsidi tepat sasaran dan mengatasi masalah struktural dalam rantai pasok. (Sumber: Perbadan 5/2024 tentang HET; Data BPS; Laporan Anggaran Bapanas)
Solusi Integratif Menuju Kedaulatan Pangan
Untuk keluar dari jerat paradoks pangan ini, Indonesia membutuhkan serangkaian solusi integratif yang menyentuh hulu hingga hilir, dengan penekanan pada pendekatan teknokratik dan solutif.
Ini mencakup tiga pilar utama: penegakan hukum yang terintegrasi dan transparansi data, disrupsi logistik melalui inovasi dan kolaborasi, serta diversifikasi pangan dan revitalisasi lumbung lokal.
Penegakan hukum tidak bisa lagi bersifat temporer, melainkan harus beralih ke pendekatan strategis dan terintegrasi.
Pertama, kita perlu melakukan audit real-time stok Bulog dan PIBC melalui platform digital. Sistem ini akan memungkinkan pelacakan kebocoran distribusi secara akurat dan meminimalisir praktik penimbunan.
Kedua, sanksi pidana harus diterapkan secara tegas bagi pelanggar mutu dan HET berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2022, termasuk pencabutan izin usaha bagi pelaku yang terbukti menyalahgunakan kewenangan. Langkah-langkah ini akan memberikan efek jera dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap mekanisme pasar. (Sumber: Perbadan 15/2022; Konsep Sistem Digitalisasi Bulog)
Selain itu, pemangkasan rantai pasok yang tidak efisien adalah suatu keniscayaan. Konsep “Koperasi Merah Putih” dapat diinisiasi sebagai hub yang menghubungkan langsung petani dengan pemerintah, sehingga mampu mengeliminasi peran tengkulak yang kerap memonopoli keuntungan.
Bersamaan dengan itu, pengembangan logistik multimodal—mengkombinasikan transportasi udara, darat, dan laut—khususnya untuk wilayah terpencil seperti Papua dan NTT, perlu dipercepat dengan pengawalan ketat dari TNI/Polri.
Hal ini akan menjamin ketersediaan pasokan dan menekan biaya distribusi secara signifikan. (Sumber: Kajian Kementan tentang Koperasi Petani; Studi Kelayakan Logistik Multimodal Papua/NTT)
Terakhir, ketergantungan pada beras adalah bom waktu yang sewaktu-waktu dapat meledak, sehingga diversifikasi pangan menjadi krusial. Potensi pangan lokal di Indonesia sangat besar, seperti varietas padi tadah hujan Inpago 13 dengan produktivitas 7,2 ton/hektare, yang membuktikan bahwa pangan lokal dapat menjadi solusi. Pemerintah perlu mengalihkan sebagian subsidi beras ke pengembangan komoditas pangan alternatif seperti sagu dan sorgum, khususnya di 100 desa rawan pangan. Lebih lanjut, revitalisasi lumbung pangan desa berbasis Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) perlu digencarkan untuk membangun ketahanan pangan lokal dan antisipasi terhadap krisis iklim. (Sumber: Data Litbang Pertanian; Program Bapanas untuk Desa Mandiri Pangan)
Jalan Berdaulat: Meninggalkan Jargon, Meraih Kedaulatan
Stok beras 4 juta ton tidak akan berarti apa-apa tanpa tata kelola yang berkeadilan. Indonesia perlu berani keluar dari jebakan kebijakan yang selama ini seolah-olah mempertentangkan kepentingan petani dan konsumen.
Langkah pertama adalah mencabut relaksasi HET dan menggantinya dengan penentuan margin distribusi maksimal 10% untuk menjaga keseimbangan harga.
Kedua, integrasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan data real-time keluarga rentan sangat krusial untuk memastikan akurasi dan efektivitas bantuan pangan.
Terakhir, transformasi Undang-Undang Pangan Tahun 2012 harus menjadi prioritas, dengan memasukkan pidana kartel beras yang lebih tegas serta insentif yang jelas bagi pengembangan pangan lokal. (Sumber: Analisis Kebijakan Ekonomi Pangan; Data DTKS Kemensos; Naskah Akademik Revisi UU Pangan 2012)
Paradoks beras yang kita saksikan saat ini adalah cermin kegagalan sistemik, bukan semata-mata kelangkaan produksi.
Jika pemerintah terus mengandalkan operasi pasar yang bersifat temporer dan relaksasi HET yang justru memicu kenaikan harga, kerugian sebesar Rp99,55 triliun akibat distorsi pasar akan menjadi bom waktu sosial yang sewaktu-waktu dapat mengancam stabilitas.
Saatnya beralih dari jargon “swasembada” menuju kedaulatan pangan berbasis desa, di mana petani mendapatkan harga yang adil dan konsumen memperoleh akses pangan yang terjangkau.
Ini adalah jalan menuju masa depan pangan Indonesia yang lebih tangguh dan berkeadilan. Tentunya kita tidak mau Indonesia Emas hanyalah sebuah mimpi .
Red/amr

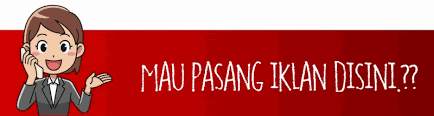



Discussion about this post